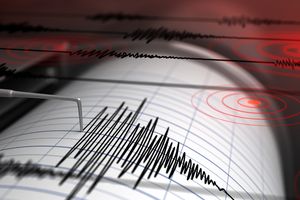Ayo Bersepeda ke Ujung Kulon!
KALI ini saya bersepeda ke ujung peradaban sebelah barat pulau Jawa. Tujuan saya adalah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Semula seorang diri saja saya jalan, tapi lalu Budi Cahya ikut. Budi adalah teman dekat semasa kuliah di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
Dulu kami sering berperahu mengarungi sungai-sungai berarus deras. Setelah lulus kuliah, lama tak bersua, kami dipertemukan kembali oleh sepeda.
Hobi ini baru digeluti Budi sekitar enam bulan terakhir. Setelah divonis menderita diabetes melitus berat lima tahun lalu, Budi mengaku sempat goyah mental. Apalagi mendiang ayahnya juga meninggal karena komplikasi penyakit akibat diabetes.
"Makan-minum jadi gak enak karena serba dibatasi. Saya malah lupa tempat gula di rumah," tutur ayah dua anak yang berprofesi sebagai kontraktor bangunan ini. Ia lalu bangkit dengan pikiran positif dan rajin olahraga, termasuk bersepeda setiap pagi keliling kompleks rumahnya di Bintaro.
Singkat cerita, kami bersepeda ke TNUK berdua. Saya tahu bersepeda sejauh sekitar 300 km ini akan berat untuk Budi. Kami persiapkan diri untuk itu dengan membawa kebutuhan dan obat-obatan yang diperlukan. Lebih dari itu, kemauan kuat Budi mengusir semua kekhawatiran. Jadilah perjalanan ini kami hayati sebagai tirakat melawan diabetes.
Kamis (20/9/2012) malam kami menumpang kereta ekonomi ke Rangkasbitung. Ada beberapa rit kereta Tanah Abang-Rangkasbitung bertarif Rp 2.000 dan yang terakhir berangkat pukul 20.30. Istirahat di sebuah losmen dekat Stasiun Rangkasbitung cukup untuk memulihkan tenaga.
Esoknya, saat fajar menyingsing, kami bergerak ke arah Pandeglang. Sekitar 20 menit jalan kami mampir warung untuk sarapan nasi uduk. Ditengah bersantap, datanglah dua gadis manis ditemani seorang pemuda.
Kedua gadis berambut lurus panjang dengan wajah lonjong, bibir tipis yang rajin senyum, dan hidung relatif mancung. Kulitnya putih bersih membalut tubuh ramping terjaga. Si pemuda juga berhidung mancung, kulit putih, rambut dan matanya kecoklatan sehingga ia dipanggil 'bule' sama temannya.
Perjumpaan dengan ketiga muda mudi ini membuka keingintahuan saya tentang Menes. Kota kecil di ruas jalan Pandeglang-Labuan melalui perbukitan Mandalawangi itu terkenal antara lain karena kaum perempuannya yang rupawan. Di kalangan masyarakat Banten sampai ada ungkapan terkenal soal Kiceup Menes atau kedipan Menes, menggambarkan kecantikan gadis Menes.
Budi yang berkampung halaman di Kampung Karamat, Cikadueun, sekitar 25 km dari Pandeglang ke arah Saketi, membenarkan hal itu. Ia mengatakan, Menes zaman dulu pernah menjadi kantong permukiman tuan tanah Belanda. Ini sejalan dengan banyaknya perkebunan di kawasan Pandeglang hingga Rangkasbitung, terutama kebun karet. Dari hasil perkawinan dengan penduduk lokal lahirlah keturunan yang memiliki ciri khas fisik blasteran.
"Sampai sekarang saya masih suka ketemu orang-orang yang mirip blasteran kalau pulang kampung. Lihat saja nanti kalau lewat," tutur Budi.
Sebagaimana dikutip http://aingorokmenes.wordpress.com/, dari beberapa literatur, ada dua peristiwa masa lalu yang memopulerkan wilayah tersebut menjadi Menes. Pertama, pada tahun 1525-1526 di wilayah tersebut bermukim seorang pedagang rempah-rempah berkebangsaan Portugis yang bernama Don Jorge Meneses atau DeMenes. Kedua, kata ‘Menes’ berarti pula tempat atau sebuah pasar untuk bertransaksi hasil perkebunan. Di tempat tersebut terdapat gudang-gudang penampungan rempah-trempah sebelum diangkut ke pelabuhan ekspor. Tempat itu disebut Blok Menes. (Ahmad Hufad dalam bukunya: Identitas Kekerabatan Orang Banten).
Tapi masih dalam buku yang sama, menurut pandangan beberapa tokoh di Menes, bahwa kata Menes bukan kata yang diserap dari bahasa Portugis, melainkan kata atau bahasa lokal, yakni mones yang berarti aneh atau keanehan.
Biasanya kata Mones dirangkai dengan awal ‘ka’ dan akhiran ‘an’ sehingga menjadi kamonesan. Artinya, keanehan, kepandaian, dan keajaiban yang cenderung bermakna khas dan unik.
Pendapat tersebut didasarkan dua alasan utama. Pertama karakter orang Menes sangat anti terhadap penjajahan orang Eropa. Sangat kuat kecenderungan mereka untuk menolak pemakaian unsur bahasa penjajah pada nama identitas komunitasnya. Kedua, kuatnya pengaruh ajaran Islam terhadap tradisi dan norma hidup dalam masyarakat Menes yang mengakar kuat dengan tradisi leluhur, terutama dalam era kesultanan sunda Islam Banten. Karena itu Menes diyakini sebagai istilah lokal yang terkait dengan mitos kejayaan leluhurnya yang aneh, ajaib, khas dan unik.
Dari alun-alun Pandeglang kami ambil jalan ke arah Saketi sampai pertigaan Mengger, sekitar 10 km di depan. Di pertigaan kami ambil jalan lurus menuju Mandalawangi.
Kalau belok kiri, jalan menuju Saketi melalui jalan raya lintas Saketi-Labuan. Kami coba jalur yang lebih kecil melintasi perbukitan Mandalawangi. Sepuluh kilometer kami mendaki jalan lurus dan berkelok-kelok yang aspalnya lumayan mulus. Asyiknya, jalan ini lalu lintasnya tak seramai jalur utama.
Selepas puncak tanjakan, jalan menurun curam dengan kelokan-kelokan tajam yang membuat kita harus waspada. Tanjakan terakhir, Cihideung lumayan terjal sepanjang dua kilometer. Kami lalu meluncur terus hingga pertigaan Jiput dan berbelok ke kiri ke arah Menes. Delapan kilometer kemudian kami masuk alun-alun Menes. Bangunan tua bekas kawedanan di salah satu sisinya kini dijadikan kantor kecamatan.
Cerita Budi soal Menes benar juga. Sepintas kami temui gadis atau pemuda dengan ciri khas blasteran berlalu di jalan. Kulit putih bersihnya agak berbeda dengan warna kulit khas orang Sunda. Kami tinggalkan Menes dan cerita tentangnya.
Jalan kecil bertemu kembali dengan jalan lintas Saketi-Labuan. Dari jalan raya kami berbelok ke arah Desa Pagelaran lalu mengambil jalan memotong lewat Kampung Ciomas, kampung halaman Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah. Sebagian jalan beton yang lama sudah hancur total. Jalan kampung itu tembus ke ruas Labuan-Tanjung Lesung.
Saat istirahat makan siang di Cibungur, sudah 76 kilometer kami bersepeda. Sekalipun mudah menemukan warung makan, sebaiknya tetap membawa bekal makanan kecil di panniers untuk bertualang di kawasan Banten Selatan ini.
Kami terus berpacu sampai Tanjung Lesung. Angin kencang dari pantai mulai menerpa, memperlambat laju kayuhan. Jalan mulus baru diaspal ternyata hanya sampai di kawasan pantai wisata.
Dari Tanjung Lesung menuju Sumur sejauh 25 kilometer jalanan rusak berat berupa tanah, pasir, dan bebatuan. Sepeda besi kami terguncang hebat dan kecepatan tinggal 8-10 km/jam saja.
Jarak yang biasanya ditempuh satu jam bersepeda harus kami lalui selama 4,5 jam. Otot-otot lengan, kaki, perut, dan punggung bekerja keras meredam getaran. Batu-batu lepas membuat traksi ban tidak mantap sehingga kami harus konsentrasi dengan handlebar. Jalan seperti ini sangat menguras tenaga.
Entah sengaja atau tidak jalan ini dibiarkan rusak bertahun-tahun. "Katanya akan ada pengaspalan 17 km, tapi tidak kunjung dilaksanakan," kata bapak pemilik warung di Kampung Cikujang.
Dengan kondisi jalan seperti ini sulit mengharapkan kawasan kaya wisata pantai ini berkembang. Jalanan melalui kampung-kampung kecil lusuh berselimut debu.
Tertatih kami susuri kampung kecil macam Kali Caah, Karang Mengpeuk, Batu Hideung, Cikujang, Kacung, Kalapa Koneng, Cemara, sampai Sumur. Garis pantai sepanjang kawasan ini sampai ke TNUK sebenarnya dianugerahkan Tuhan dengan keindahan alami. Namun bagaimana bisa menjadi obyek wisata unggulan dengan akses jalan seburuk ini? Apakah memang disengaja seperti ini untuk melindungi keasrian TNUK? Alih-alih memperbaiki jalan ini, pemerintah malah mau membangun jalan membelah kawasan dengan dalih konservasi badak.
Baru pukul 19.30 kami tiba di Sumur, saat sebagian besar toko sudah tutup. Total kami menempuh jarak 123,20 kilometer dari Rangkasbitung.
Budi terlihat kelelahan namun hatinya senang. Dia lupa membawa alat pengukur kadar gula tubuh, tapi melihat raut muka, sorot mata, dan bahasa tubuh lainnya saya yakin dia baik-baik saja.
Sumur adalah ibu kota kecamatan yang lumayan ramai. Banyak penginapan murah karena tempat ini juga menjadi basis penyeberangan wisata ataupun memancing di perairan TNUK.
Istirahat semalam cukup untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Sabtu (22/9/2012) pagi kami genjot sepeda dengan hati riang ke arah barat menuju Desa Taman Jaya, Ujung, dan berakhir di pantai Legon Pakis di dalam kawasan TNUK. Di sepanjang jalan sawah-sawah kering kerontang dan pepohonan meranggas. Kemarau panjang sudah berlangsung lebih dari empat bulan di kawasan ini menyisakan pemandangan nan gersang.
Kondisi jalan masih sama buruknya dengan kemarin. Jarak 25 km kami tempuh dalam waktu 4,5 jam penuh prahara diatas sadel. Pantat yang sudah kapalan sekalipun bakal nyeri dengan guncangan seperti ini. Tapi semangat kami tetap membara untuk sampai di ujung jalan. Melintasi sejumlah kampung, bau asap kayu bakar merebak di udara yang kering. Persawahan tadah hujan meranggas dimana-mana karena sudah tiga bulan tak kunjung hujan.
Sebagian penduduk menjemur kopra untuk diangkut ke Labuan, memecah batu, menambang pasir di sungai-sungai kecil, dan menjemur ikan hasil tangkapan di laut. Lainnya duduk di teras atau menjaga warung. Mereka menyapa kami dengan ramah dan santun.
Untuk mengusir jenuh, saya ajak sekelompok anak Kampung Cigorowong bersepeda bareng. Tujuh anak usia 10-11 tahun yang menamakan kelompoknya 'Tarik Gowes' itu ternyata jago kebut dengan bmx di jalanan berbatu. Senang melihat kelincahan dan polah mereka yang riang gembira diatas sadel, ngebut saling susul, meninggalkan debu beterbangan.
Akhirnya tibalah kami di pintu masuk TNUK. Tugu badak yang bagian culanya sudah rompal dan tulisan 'Welcome to Ujung Kulon' menyambut bisu. Angin panas menerbangkan butiran pasir halus yang melekat di rumah-rumah dan pepohonan di pinggiran jalan.
Pak Abun, jagawana yang berjaga di Pos PHPA Legon Pakis memberitahu bahwa karcis masuk TNUK seharga Rp 2.500 ditambah asuransi Rp 3.000 dibayar di Pos PHPA di Desa Taman Jaya. Tak ada petunjuk apa pun saat kami tiba di Taman Jaya sehingga kami terus saja masuk ke dalam kawasan TNUK.
Matahari beranjak ke ubun-ubun saat kami tiba di Kampung Legon Pakis di dalam kawasan TNUK. Itulah peradaban terakhir di batas hutan dan pantai ujung barat Pulau Jawa. Kampung itu berupa kumpulan 30-an rumah disela-sela pohon kelapa. Pengunjung TNUK biasa bermalam di rumah-rumah warga atau Pos PHPA di kampung itu. Kalau mau, bisa juga berkemah di kawasan hutan.
Di pinggiran pantai kami bongkar logistik dan memasak. Keheningan hutan ditingkahi debur ombak kecil mengobati penat sepanjang jalan. Sore hari kami kembali ke Sumur dan bermalam lagi.
Minggu (23/9/2012) perjalanan pulang ke simpang Tanjung Lesung-Citeureup kami tempuh melalui Cibaliung, melintasi jalan turun-naik mendaki perbukitan. Jaraknya memang lebih jauh yaitu 46 km, tapi kondisi jalannya mulus. Ada jalur lain yang lebih pendek sekitar 25 km yaitu melalui Cigeulis, namun saat ini jalan tembus yang di dekat Sumur masih dibangun.
Di rumah Budi memeriksa kadar gula darahnya saat puasa ternyata 114 (dengan ambang batas 110-120) dan badannya segar bugar. Tirakat kami ke barat berakhir disini... (Max Agung Pribadi)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.