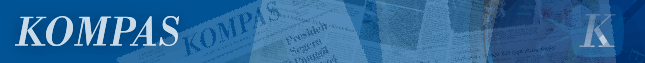Syahdan, tersebutlah Bowak, seorang manusia yang diculik para penguasa kayangan atau dunia atas yang penuh kemakmuran. Di alam atas, Bowak akhirnya mengetahui asal-usul kekayaan dunia atas. Bowak melihat bagaimana sebuah benda bernama ”mihing” selalu penuh belanga berisi beraneka permata dan emas dari dunia manusia.
”Ketika para penguasa dunia atas membuat mihing baru, Bowak diikat di tempat yang jauh. Bowak berteriak, ia melihat para penguasa kayangan membuat mihing. Ketika dikurung di bawah sebuah gong raksasa, Bowak mengaku melihat cara membuat mihing. Ia mengaku tak bisa melihat jika matanya ditutupi jaring penangkap ikan. Maka, wajahnya pun ditutupi jaring ikan,” tutur Yemima Yulita, Kepala Seksi Sarana Promosi Dinas Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah.
Yemima menuturkan legenda Dayak Ngaju itu di samping replika sebuah mihing, berupa jalinan delapan jenis rotan dan kayu yang membentuk sewujud rangka kapal tanpa dinding setinggi 1,5 meter. Panjang replika mihing koleksi Museum Balanga di Palangkaraya itu sekitar 10 meter. Ukuran aslinya bisa mencapai 10 kali ukuran replika itu.
”Bowak yang kembali ke alam manusia membuat mihing dan menanamnya di dasar sungai, dan mihing selalu mendatangkan banyak ikan. Kekuatan magis mihing, antara lain, diyakini berasal dari kayu tawe, kaja, tabulus, banuang, dan puri yang diukir sebagai patung yang berjajar di ’pintu mihing’. Patung-patung yang mengundang dan mempersilakan ikan-ikan untuk masuk ke dalam mihing. Mihing adalah salah satu lambang filosofi orang Dayak yang erat terkait dengan budaya sungai,” kata Yemima.
Lantai dua Museum Balanga penuh koleksi yang menunjukkan kedekatan orang Dayak dengan sungai. Sebuah lanting atau rumah terapung berisi beragam alat penangkap ikan. Terdapat berjenis-jenis tombak ikan mulai dari sahimpang, sahimpang banan, bahola, hingga pakihu. Juga berjenis-jenis pancing, bubu penangkap ikan, hingga aneka jala yang dirajut dari tali berbahan kulit dan akar pohon.
Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Sabran Achmad menyebut lanting, rumah apung ”berfondasi” batang-batang kayu besar itu, sebagai kearifan lokal masyarakat adat Dayak dalam menyelaraskan hunian dengan kondisi alam. ”Batang-batang yang menjadi fondasi lanting memungkinkan rumah tersebut dapat mengapung mengikuti pasang surut muka air sungai. Lanting tak pernah kebanjiran,” kata Sabran.
Dari 74,3 juta hektar luas Pulau Kalimantan, seluas 53,7 juta hektar menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Di dalam 53,7 juta hektar itu, mengalirlah berpuluh-puluh sungai raksasa, termasuk Sungai Kapuas di Kalimantan Barat (1.143 kilometer), Sungai Barito di Kalimantan Tengah (880 kilometer), dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur (980 kilometer).
Sungai-sungai tersebut masing-masing memiliki anak-anak sungai, tempat manusia Dayak tinggal dengan segenap tradisi sungainya. Sabran menyebutkan, di Kalimantan Tengah saja orang Dayak terbagi dalam empat suku induk: Ngaju, Ot Danum, Lawangan, dan Maanyan. ”Dari empat suku besar ini, ada 131 anak suku. Tiap wilayah yang dibatasi anak sungai mempunyai adat istiadat, martabat, dan tingkah laku sendiri. Itulah yang disebut anak suku tadi,” ujar Sabran.
Antropolog Marko Mahin mengatakan begitu vitalnya peranan sungai dalam menghimpun beratus-ratus anak suku Dayak sehingga sungai-sungai di Dayak membentuk identitas bersama orang Dayak yang berada di daerah aliran sungai (DAS) yang sama. ”Ketika disebut orang Barito atau orang Kahayan, mereka merasa satu. Itulah yang kerap diistilahkan sebagai politik aliran. Aliran DAS mempersatukan,” kata Marko.
Meski demikian, di satu DAS yang sama, tidak mesti punya sistem nilai dan tradisi yang sama. Dalam satu sungai, ujar Marko, transaksi budaya di antara kelompok bisa terjadi. Dalam beberapa catatan, orang dari hulu yang sedang paceklik bisa ke pesisir untuk ikut panen. Ini karena antara hulu dan muara beda masa panennya. Warga yang tinggal di muara biasa bersawah karena wilayahnya pasang surut. Mereka panen sekitar bulan Agustus-September. Adapun warga di hulu yang berladang musim panennya sekitar bulan Juni-Juli.
Sungai bukan sekadar identitas ataupun sumber kemakmuran bagi orang Dayak. ”Orang Kalimantan mengenal danum kaharingan atau air kehidupan. Mereka melihat sungai merupakan bagian dari air kehidupan. Dalam konsep danum kaharingan ini, orang yang mati kalau dipercikkan air itu bisa kembali. Dalam beberapa cerita rakyat, kembali itu bisa di alam berikutnya (surgaloka) atau di alam nyata ini,” kata Marko.
 Sejumlah warga menikmati suasana pagi sembari menyantap menu khas Banjar di warung yang memanfaatkan bangunan rumah lanting di tepi Sungai Martapura, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.
Sejumlah warga menikmati suasana pagi sembari menyantap menu khas Banjar di warung yang memanfaatkan bangunan rumah lanting di tepi Sungai Martapura, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.”Dunia atas dan dunia bawah saling melengkapi. Bisa dibedakan, tak bisa dipisahkan. Manusia ada di dunia tengah. Di dalam konsep orang Dayak, orang naik ke surga juga melalui sungai. Tidak sekadar ada di alam manusia, sungai merupakan jalan masuk ke dunia bawah ataupun dunia atas,” ujar Marko.
Sungai menjadi bagian dari kehidupan manusia Dayak mulai dari tarikan napas pertamanya, bahkan hingga selepas embusan napas terakhirnya. (Aryo Wisanggeni G/C Anto Saptowalyono/Putu Fajar Arcana)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.