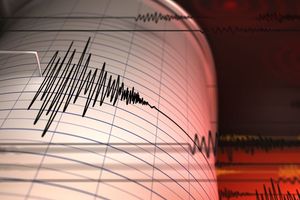Titik Nol (204): Kamp Pengungsi
Apa yang saya cari? Pertanyaan ini pun sering menghantui saya dalam perjalanan ini. Apa yang saya cari, di tempat-tempat berdebu dan panas, yang orang pun malas untuk membayangkannya. Saya sering bergulat dengan pertanyaan yang satu ini. Sering kali orang yang bertanya tak bisa mengerti pula penjelasan saya. Ini adalah pertanyaan, yang sering ditanyakan dengan serius, namun kemudian berakhir dengan mengambang begitu saja di udara, hanya menjadi penghias percakapan belaka.
Adalah sebuah mimpi yang membawa langkah-langkah saya hingga ke sini. Mimpi untuk menyingkap rahasia Afghanistan, yang selama ini selalu tersembunyi di sudut angan, terbungkus selimut debu dan lekukan gunung-gunung tinggi. Afghanistan dalam benak saya, adalah barisan orang-orang bersurban yang melindungi gunung-gunung gundul tak bertuan. Sejarah yang membasuh bumi Afghan dengan darah, selalu membuat negeri ini sangat misterius.
Tiga tahun lalu, dengan mimpi yang sama, saya datang di hadapan Khalif. Dengan bahasa Urdu saya yang ala kadarnya, akhirnya Khalif menangkap maksud saya. Kecintaan yang sama tentang negeri yang sama, Afghanistan – di balik gunung sana.
Senyumnya yang manis tersungging dari balik jenggot tipisnya.
Khalif kemudian menceritakan tentang kampung halamannya di Jalalabad. Panasnya memang membakar kulit, tetapi hijaunya lembah yang dipenuhi anggur dan melon yang manisnya luar biasa itu ibarat surga di bumi. Khalif, seorang dari jutaan pengungsi Afghan di Pakistan, sudah lama menetap di Peshawar. Namun sesekali ia pulang ke Jalalabad.
"Afghanistan sekarang sudah lebih baik," kata Khalif.
"Tidak. Peshawar masih jauh lebih baik."
Pulang, mungkin memang kata terakhir yang terbersit di pikiran Sher Shah, 22 tahun, seorang pengungsi, juga dari Jalalabad di bagian timur Afghanistan. Kampung halaman sudah bukan lagi kebun anggur yang indah. Dalam bayangannya yang ada hanyalah puing-puing dan kehancuran.
"Mengapa harus pulang? Kami sudah tidak punya tanah, tidak ada rumah, tidak punya apa-apa lagi. Apa lagi yang bisa kami kerjakan? Apa lagi?"
Bukankah Peshawar adalah kota yang nyaman? Mereka semua berbicara bahasa Pashtun, sama dengan yang ada di Afghanistan. Jalan-jalan lebar dan mulus. Mobil-mobil berlalu lalang. Pasar-pasar selalu hiruk pikuk. Tak ada perang dan ketakutan. Belum lagi gadis-gadis bisa pergi sekolah dengan bebas. Walaupun harus tinggal di rumah-rumah lumpur yang kotor, bagi Sher Shah, Peshawar adalah rumahnya.
Kamp pengungsi Kacha Garhi di distrik Hayatabad tak jauh dari pusat kota Peshawar, tempat sekarang Sher Shah tinggal, memang sudah ada lebih dari 25 tahun lalu. Waktu itu, tentara-tentara kulit putih dari Rusia sudah menduduki Kabul. Afghanistan ikut berkibar bersama merahnya panji-panji komunis Uni Soviet. Tanah Afghan pun bersamanya menjadi merah, karena darah mengalir di mana-mana.