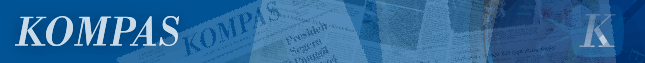Pengaruh zaman nyata pula pada batik Belanda. Batik yang diproduksi pengusaha Indo-Belanda dengan pembatik-pembatik pribumi ini bercitarasa Eropa, diproduksi sekitar tahun 1840-1910. Pembatik Jawa yang bekerja untuk para noni Belanda dapat menuangkan dongeng populer Eropa, seperti ”Putri Salju”, ”Hanzel dan Gretel”, dan ”Kisah si Topi Merah”, menjadi motif batik. Batik Metzelaar dan Van Zuylen yang terkenal dengan ragam hias halus juga bisa dinikmati di sini.
Pada masa penjajahan, dibuat pula batik Perang Diponegoro. Namun, yang termuat sebagai motif hanya gambar tentara kompeni dan persenjataan mereka. Tidak ada gambar Pangeran Diponegoro dan pasukannya.
Sebelum tahun 1910, batik yang dibuat pengusaha keturunan China memuat ragam hias binatang dari mitos China, seperti naga, burung hong, dan singa berkepala anjing. Setelah tahun 1910, batik China mengadopsi motif bunga, dedaunan, dan kupu-kupu dari batik Belanda. Pada batik China dikenal istilah batik ”Tiga Negeri” dengan motif yang memuat warna merah, biru, dan soga.
Tiap lembar kain batik Tiga Negeri diwarnai di tiga daerah. Motif merah diwarnai di Lasem, biru di Kudus atau Pekalongan, sedangkan soga di Surakarta atau Yogyakarta. Bayangkan jarak yang mesti ditempuh untuk membuat selembar kain batik di zaman ketika kemudahan transportasi masih jauh dari bayangan.
Di sejumlah daerah, batik mempunyai kekhasan corak dan warna tersendiri. Semua menyimpan cerita. Melihat keindahan batik yang bernilai seni tinggi tidak akan lengkap tanpa memahami pula bagaimana proses produksinya. Museum ini menunjukkan pula tahapan dari kain mori putih hingga jadi batik, serta bahan–bahan yang dibutuhkan untuk itu.
Perjalanan melihat kemegahan warisan budaya meninggalkan bekas lebih dalam di hati ketika kami mencoba mengguratkan malam (lilin) batik dengan canting bersama para pembatik di bengkel kerja yang ada di belakang museum. Terdapat sekitar 300 pembatik yang bekerja memproduksi batik tulis dan cap di bengkel itu.
Bau malam yang dipanaskan dengan tungku-tungku kecil sungguh menggoda. Namun, melukiskan pola batik sederhana sekalipun sungguh tak mudah bagi tangan yang tak biasa. Sungguh warisan budaya yang berharga. (Nur Hidayati)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.